 Abiyyu Rifqi
Abiyyu Rifqi
Politik | 2025-10-18 19:45:09

Di era globalisasi yang semakin terkoneksi, kekuatan sebuah negara tidak lagi hanya diukur dari jumlah pasukan militer atau kekuatan ekonominya, tapi juga dari sejauh mana budaya mereka mampu memengaruhi dunia. Fenomena ini disebut soft power, sebuah bentuk kekuasaan yang bekerja diam-diam melalui daya tarik budaya, ide, dan nilai-nilai yang dikemas dengan sangat halus. Dari K-pop Korea Selatan sampai film Hollywood Amerika Serikat, ekonomi budaya kini telah menjadi senjata diplomasi yang efektif—membentuk persepsi global dan bahkan mengubah tatanan politik dunia.
Hollywood sudah lama menjadi alat diplomasi Amerika Serikat. Sejak Perang Dingin, film dan musik menjadi sarana penyebaran nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan individualisme yang melekat kuat pada identitas Amerika. Film seperti Top Gun atau Captain America bukan sekadar hiburan, tapi juga alat pembentukan citra nasional yang memperlihatkan kekuatan militer, moral, dan kepemimpinan global AS. Melalui film, AS membangun narasi bahwa mereka adalah “pahlawan dunia”, simbol modernitas dan kemajuan yang ingin ditiru banyak negara.
Tapi di abad ke-21, Korea Selatan muncul sebagai pemain baru yang mampu menandingi dominasi budaya Barat. K-pop, drama Korea, dan industri hiburan mereka bukan hanya soal musik dan tontonan; ini adalah bentuk diplomasi budaya yang dikonsep secara strategis oleh negara. Pemerintah Korea Selatan secara aktif mendukung industri hiburan melalui kebijakan ekonomi kreatif, promosi internasional, dan kolaborasi global. Hasilnya luar biasa: dari BTS hingga Squid Game, budaya Korea menjadi wajah baru Asia di mata dunia.
Di sinilah kekuatan soft power bekerja bukan lewat paksaan, tapi lewat daya tarik. Ketika dunia mencintai budaya Korea, mereka juga, secara tidak langsung, menerima nilai-nilai yang dibawa: kerja keras, kolektivitas, dan semangat nasionalisme modern yang dikemas dengan gaya pop.
Fenomena ekonomi budaya tidak bisa dilepaskan dari logika pasar global. Budaya kini bukan sekadar ekspresi identitas, tapi juga komoditas bernilai tinggi yang mampu menghasilkan keuntungan besar sekaligus memperluas pengaruh politik. Contohnya, ekspor budaya Korea mencapai miliaran dolar per tahun, memberi dampak langsung pada sektor pariwisata, perdagangan, hingga diplomasi publik.
Begitu juga dengan Jepang lewat anime dan pop culture-nya yang berhasil memulihkan citra negara pasca Perang Dunia II. Mereka menunjukkan bahwa budaya bisa menjadi jalan untuk membangun kembali reputasi dan pengaruh global tanpa perlu konfrontasi politik. Bahkan Tiongkok kini mulai meniru strategi serupa dengan mempromosikan konsep “China Dream” melalui film, aplikasi, dan media digital buatan mereka sendiri.
Namun, di balik keberhasilan itu, ada dinamika politik yang menarik. Negara-negara menggunakan budaya bukan hanya untuk memperkenalkan diri, tapi juga untuk membingkai narasi tertentu di kancah global. Hollywood, misalnya, sering menampilkan Amerika sebagai penjaga tatanan dunia, sementara musuhnya digambarkan dengan stereotip tertentu. Di sisi lain, produk budaya Korea sering membawa citra “Asia modern” yang ingin menegaskan posisi kawasan Timur di dunia global.
Budaya bukan lagi milik seniman atau masyarakat semata; ia telah menjadi alat negara. Siapa yang mampu menjadikan budayanya tren global, dialah yang memenangkan hearts and minds masyarakat dunia.
Namun, tidak semua pihak menyambut ekonomi budaya dengan tangan terbuka. Di banyak negara, ekspansi budaya asing justru dianggap sebagai bentuk cultural imperialism — penjajahan gaya baru yang menembus batas tanpa senjata. Misalnya, dominasi budaya Barat sering dianggap mengikis nilai-nilai lokal dan memunculkan ketergantungan identitas. Di sisi lain, ketika budaya Asia mulai bangkit dan diterima global, muncul kekhawatiran di Barat tentang “pergeseran pengaruh” ke Timur.
Fenomena ini membuat budaya menjadi medan baru perebutan kekuasaan global. Negara-negara berlomba untuk “menjual citra” mereka lewat seni, mode, musik, dan digital content. Diplomasi budaya menjadi bagian dari strategi besar yang disebut nation branding — bagaimana sebuah negara membangun reputasi positif di dunia.
Namun, di tengah persaingan itu, muncul pertanyaan penting: apakah ekonomi budaya benar-benar bisa membawa dialog antarbangsa, atau justru memperdalam kompetisi global dalam bentuk yang lebih halus?
Kekuatan budaya yang awalnya dimaksudkan untuk mendekatkan bangsa, kini juga bisa menjadi alat persaingan. Ketika nilai-nilai dikomodifikasi dan dijadikan instrumen ekonomi, ada risiko budaya kehilangan esensinya. Diplomasi budaya yang seharusnya menghubungkan, bisa berubah menjadi ajang dominasi simbolik.
Dunia kini hidup dalam era di mana video musik bisa lebih berpengaruh dari pidato politik, dan influencer bisa punya dampak lebih besar dari diplomat. Dalam konteks ini, ekonomi budaya adalah kekuatan baru yang tak bisa diabaikan. Tapi keberhasilan sebuah negara dalam memainkan soft power-nya tetap bergantung pada satu hal: keaslian.
Korea Selatan berhasil bukan hanya karena produknya populer, tapi karena mereka membangun budaya yang autentik dan relevan. Sementara Amerika Serikat, meski masih menjadi pemain utama, kini harus menghadapi dunia yang lebih kritis terhadap narasi hegemoninya.
Ke depan, budaya akan terus menjadi medan strategis dalam politik global. Tapi semoga, di tengah kompetisi dan komodifikasi, kita tak lupa bahwa esensi budaya adalah untuk menghubungkan manusia bukan menguasainya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 3 hours ago
2
3 hours ago
2





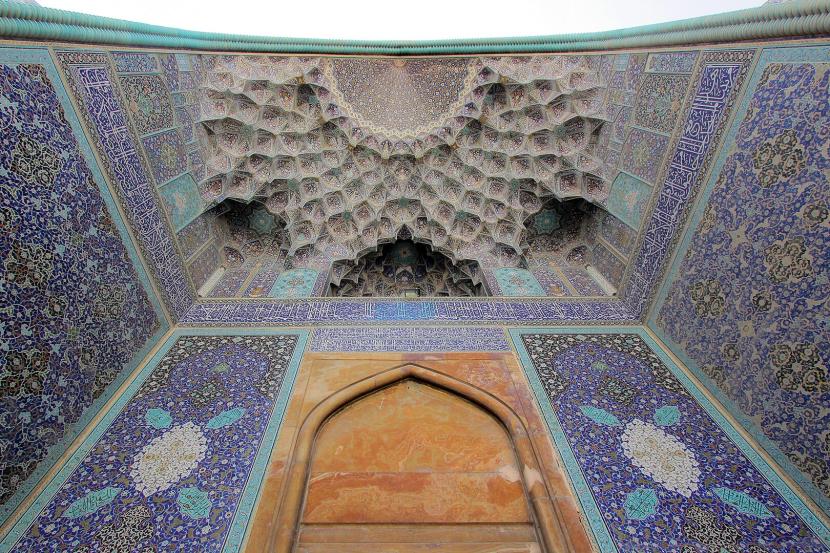






















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5247874/original/059845100_1749548280-sambal-goreng-hati-sapi-dan-kentang-foto-resep-utama.jpg)








:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5135897/original/040885100_1739796434-Pisau_dapur_3.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5234933/original/091236300_1748405304-ChatGPT_Image_28_Mei_2025__11.06.52.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4952970/original/061900600_1727263483-delicious-mezcal-beverage-composition.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5175684/original/053318300_1743044742-WhatsApp_Image_2025-03-27_at_09.51.03.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4852706/original/063786400_1717495529-IMG_2688.jpeg)